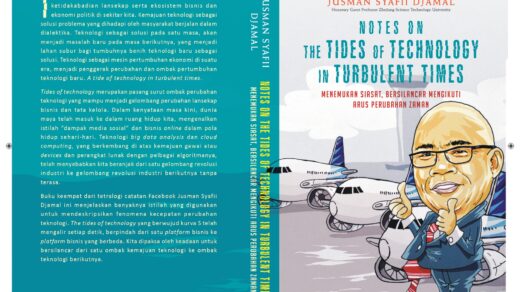JEJAK PAJAK INDONESIA
JILID 1: ABAD KE-7 SAMPAI 1966
Bab 1 Kedatuan Sriwijaya
Sriwijaya mengendalikan rute perdagangan rempah-rempah dari dan ke Cina, India, hingga Arab, termasuk rute perdagangan lokal. Sriwijaya mengenakan cukai pelabuhan dan pajak penimbunan barang untuk orang asing atas tiap kapal yang melewati wilayah kekuasaannya di Selat Malaka.
Setiap kapal niaga yang melalui selat tersebut harus membayar cukai kepada Sriwijaya sebagai penguasa selat. Di kawasan selat dan kerajaan maritim, terdapat aturan tak resmi bahwa penyerangan atas kapal dagang dapat terjadi jika mereka tidak mau bersandar atau membayar pajak pelayaran (upeti) di wilayah kekuasaan kerajaan yang dilalui. Jadi, kapal-kapal seperti dari Tiongkok yang melalui wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya membayar pajak setiap kali melintas. Kas Kerajaan Sriwijaya pun diisi oleh bea masuk barang dagangan yang melewati pelabuhannya. Selain bea masuk, Kerajaan Sriwijaya juga mendapat pemasukan dari bea kapal berlabuh, upeti persembahan dari para pedagang dan raja-raja taklukan, serta keuntungan perdagangan yang dilakukannya.
Pemasukan pada kas kerajaan menjadi penting karena pos-pos pengeluaran sangat mengandalkan pemasukan tersebut. Misalnya, pembiayaan tentara kerajaan pusat di Palembang dibayar dari hasil pajak kekuasaan dan penerimaan perdagangan.
Bab 2 Kerajaan Mataram Kuno
Konsep pajak di tanah Jawa berbeda dengan di Sumatera. Pada masa Mataram Kuno di abad ke-7, yang semasa kejayaan Sriwijaya, di Jawa diterapkan konsep Dewa Raja, bahwa raja adalah jelmaan dewa dan diakui sebagai penguasa tunggal, hingga berhak melakukan pungutan dari penduduk untuk penyelenggaraan pemerintahan, yang pada masa itu tidak dalam bentuk uang melainkan barang.
Kata kunci konsep pajak zaman ini adalah Drabya Haji, dari kata Drawya yang berarti milik, dan Haji yang berarti raja, dimaknai kekayaan milik raja, termasuk pajak yang dipungut atas tanah, karena raja sebagai pemegang hak atas tanah, dan rakyat hanya mengolah bukan memiliki, karena itu pajak dikenakan atas mereka sebagai pungutan rutin. Jenis pajak pada masa Mataram Kuno berdasarkan obyek pajak meliputi pajak tanah, pajak usaha, pajak orang asing dan pajak lainnya. Pejabat pemungut pajak ada yang disebut Manak Katrini dan Sang Manilala Drawya Haji.
Faktor pengurang pungutan pajak adalah penetapan daerah perdikan yang disebut sima, yakni daerah yang atas anugerah raja ditetapkan bebas dari kewajiban membayar pungutan pajak. Selain ditetapkan, rakyat dibolehkan mengajukan wilayah yang tidak mampu bayar pajak untuk dijadikan sima. Dalam sima, rakyat boleh melakukan kegiatan bisnis, dan sering menguntungkan. Untuk meminimalisir potensi kehilangan pembayaran pajak, raja dapat membatasi jumlah usaha pada suatu sima, yang jika melebihi batas ketetapan jadi dikenakan pajak. Pajak dari kegiatan usaha ini tak butuh waktu lama menunggu hasil panen, seperti pada pajak tanah.
Bab 3 Kerajaan Kahuripan
Kerajaan Kahuripan memiliki filosofi Dewa Surya, laksana matahari menghisap air perlahan untuk dicurahkan kembali ke bumi sebagai hujan. Filosofi ini diterapkan sebagai pemungutan pajak yang sedikit demi sedikit dan tidak memberatkan.
Konsep pemungutan pajak masih serupa zaman Mataram Kuno, yaitu Drawya Haji yang dipungut oleh Manilala Drawya Haji sebagai pemungut pajak. Airlangga menjalin banyak hubungan baik dengan kerajaan lokal dan mancanegara, karena itu ia banyak pula memungut pajak orang asing demi turut membangun negara. Begitupun para pekerja asing, dikenakan pajak atas penghasilannya. Sumber pemasukan lainnya dari denda atas tindak pidana yang disebut Sukhadukha meliputi 18 macam tindak pidana. Pidana tersebut dapat ditebus dengan membayar sejumlah denda dalam bentuk uang emas, kecuali pencurian dan perampokan yang dikenai hukuman mati. Banyaknya reformasi yang dilakukan Airlangga menjadikannya disebut sebagai pembaharu pada abad ke-10.
Bab 4 Kerajaan Majapahit
Model birokrasi dan sumber pemasukan negara Majapahit melalui pajak masih serupa pendahulunya, namun perbedaan penting terletak pada mulai digunakannya uang sebagai alat tukar. Sebagai negara agraris dan perdagangan, Majapahit mengandalkan pendapatan dari hasil bumi serta pajak. Pajak tanah diatur lebih ketat dalam hal pemanfaatan yang lebih intensif. Selain dikenakan pajak atas hasil buminya, juga dikenakan denda jika rakyat menelantarkan tanahnya.
Pemasukan Majapahit banyak melalui upeti yang dipersembahkan oleh kerajaan lain yang bernaung di bawah panji Majapahit. Pajak irigasi juga jadi ciri lain dari kerajaan Majapahit, selain pajak usaha, pajak perdagangan, pajak kerajinan dan pajak pemilikan usaha transportasi bisnis. Pajak orang asing yang berkegiatan usaha memberi perlindungan kepada para pedagang pribumi untuk dapat bersaing dan menggeliatkan ekonomi kecil.
Bab 5 Kerajaan-Kerajaan di Pesisir
Kerajaan pesisir antara lain Samudera Pasai, Aceh, Demak, Banten, Ternate, Gowa Tallo, dan Bone. Ciri khas pungutan kerajaan-kerajaan di wilayah pesisir adalah pajak dan bea cukai yang terpusat di pelabuhan-pelabuhan utama sebagai gerbang ekspor dan impor barang. Barang-barang ekspor impor di pelabuhan diukur dan ditimbang dengan tarif berbeda sesuai jenis barang dan daerah asal. Misalnya, barang dari Arab, Srilanka, India, Pegu dan Siam, dikenakan besaran pajak impor 6%. Namun, bahan makanan dari Pegu dan Siam bebas pajak impor meski tetap wajib memberi persembahan.
Negara dari dunia barat dikenakan pajak tambahan 3% dari pungutan 6%, sementara dari Melayu 3% ditambah 3%. Dari Nusantara serta Asia Timur tak dipungut pajak, diganti dengan pemberian hadiah.
Bab 6 Kesultanan Mataram Islam
Pada masa kesultanan, wilayah Mataram dibagi menjadi empat yakni Kutharaja (kompleks keraton), Negaragung, Mancanegara, dan daerah pesisir. Tanah yang dikuasai kerajaan ini dinamakan lungguh, dengan petugas bekel yang bertanggung jawab menarik pajak di setiap desa.
Istilah “pajeg” yang serupa maknanya dengan pajak diperkenalkan di era Kesultanan Mataram Islam. Kewajiban membayar pada negara berupa uang atau barang lainnya. Terdapat tak kurang 37 jenis pajak, termasuk bentuk sumbangan atau pundutan, sebagai wujud bakti kepada raja. Pajak yang paling penting adalah pajak bumi, berdasar perkiraan produktivitas hasil panen rata-rata, sebesar sepertiganya. Ketika Mataram Islam berada di bawah kekuasaan VOC, dikenal jenis pajak “kuota padi”, yang ditarik dari penduduk yang mengolah sawah. Selain itu, pajak atas pedagang dan pengrajin usaha dibayar dalam bentuk uang.
Pada masa Amangkurat II (1677-1703), Mataram Islam menetapkan pajak cukai untuk wilayah pesisir demi menyaingi pungutan pajak oleh VOC. Nilainya 3-6% dari nilai barang dagangan dengan rata-rata 4%. Bea juga dikenakan tak hanya di pesisir melainkan di pedalaman, untuk membedakan dengan pajak tetap/pajeg. Bea dipungut sebagai tambahan misal jaminan keamanan pada pasar atau bandar.
Pada era Mangkunegaran berdiri Dinas Perpajakan yang mengelola seluruh jenis pajak yang ditarik dari rakyat, dan diatur dalam regulasi pajak di lembaran kerajaan. Pada era Mangkunegara VI (1898-1916), jenis pajaknya meliputi pajak bumi, pajak tanah dalam kota, pajak tanah asing, pajak kepala, pajak penghasilan, pajak minuman keras, pajak mercon, pajak tontonan, pajak krisis, hingga pajak motor dan kereta.
Bab 7 Kedatangan Portugis
Kerajaan Sunda meminta bantuan Portugis, yang disepakati dengan imbalan seribu karung lada tiap tahun pada tahun 1522. Portugis juga terlibat pembangunan benteng di Sunda Kelapa. Setelah tahun 1545, Portugis mulai mendapat keuntungan mengapalkan 1,5 juta kg lada per tahun ke Cina dan India dari Banten setelah benteng berdiri.
Terkait perpajakan, pendudukan Portugis di Malaka menerapkan pajak ekstra pada kapal Melayu, yang disebut ruba-ruba sebesar 1 real per kapal, yang dikecualikan bagi orang Jawa, Malaka, dan orang asing. Kapal yang keluar masuk juga harus memiliki pas berlayar dengan wajib membayar ¼ real. Pajak tanah juga dikenakan sebesar 12%, sepertiganya berbentuk lada dan dua per tiganya tunai. Selain itu, pajak impor bagi pedagang swasta dari India dan Carreira diterapkan sebesar 30%, yang dianggap mencekik. Pajak tinggi yang dikenakan Portugis membuat kapal-kapal dagang mulai beralih ke rute baru lewat Aceh, lalu menyusuri pantai barat Sumatera. Mereka tidak lagi melewati Selat Malaka untuk menuju ke Banten.
Di Malaka, banyak daerah menetapkan pajak lebih besar dari 6%, yang menumbuhkan diskriminasi terhadap barang dari daerah tertentu. Pajak 8% diterapkan untuk pedagang Pegu Sumatera, Singapura, dan Sabah, serta 12% untuk pedagang India kecuali Bengal. Serangan VOC Belanda pada 14 Januari 1641 meruntuhkan kekuasaan Portugis di Nusantara.
Bab 8 Kekuasaan VOC (1602-1799)
Pemerintah kerajaan Belanda memberi hak istimewa atau hak Oktroi kepada VOC untuk memonopoli perdagangan, mengadakan perjanjian, hingga diberi kekuasaan kehakiman, pemungutan pajak, dan membentuk pemerintahan sendiri termasuk angkatan perangnya. Sistem Leverantie dan Contingenten dikeluarkan oleh VOC terhadap Banten. Isinya pengenaan pajak setinggi mungkin dan pemaksaan penjualan hasil pertanian lada dan rempah-rempah.
Tragedi Angke, yakni pembantaian 10.000 lebih orang Tiongkok tahun 1740 oleh VOC berdampak serius terhadap berkurangnya pemasukan kas dari sisi pacht alias Pajak. Hampir tiap jenis pajak di Batavia dibayar oleh etnis Tionghoa yang mayoritas pedagang dan penyewa lahan. Mereka juga membayar Pajak Kepala sebesar 1 real per bulan, di samping pajak rumah perjudian, pajak arena adu ayam, hingga pajak perahu junk dari Tiongkok yang berkunjung ke pelabuhan. Untuk mengatasinya, sejak 1743 etnis Cina ditempatkan di kawasan khusus Glodok dekat pusat pemerintahan agar dapat diawasi langsung oleh VOC. Mereka dikenakan pula pajak kuncir, pajak kepala, pajak babi, hingga pajak kuda dan kereta.
Mataram kemudian memberi VOC konsesi ekonomi, seperti pembebasan dari bea dan cukai, serta diberi izin tinggal dan mendirikan pos-pos militer di pesisir dan pedalaman. Tak kurang dari 1.653 pos pajak didirikan sebagai lumbung utama pendapatan VOC, dengan 27% kontribusinya bersumber dari pajak peternakan. VOC juga mengenakan pajak beras yang ditetapkan kolektif untuk seluruh desa.
Bab 9 Kekuasaan Prancis (Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels 1808-1811)
Daendels meletakkan dasar sistem pajak bumi (pajak hasil tanah) atau landrente. Di hadapan para bupati, Daendels mengumumkan tentang penghentian semua penyetoran hasil bumi dan menggantinya dengan pajak, upeti, cukai, dan biaya pengakuan.
Adapun jenis pajak lainnya yang bisa ditemukan pada periode Daendels meliputi: (1) pajak tanah; (2) pajak pacumpleng atau pajak atas pintu; (3) pajak lerog-aji atau pajak perorangan; (4) pajak pengawang-awang atau pajak pekarangan; (5) pajak pajigar atau pajak atas jumlah kerbau, sapi, dan kuda; (6) pajak wilah welit atau pajak sawah per-jung per tahun sebesar florin 2,50; (7) pajak pajungket atau pajak atas pindah rumah; dan (8) pajak bekti atau uang pajak untuk menerima tanah jabatan.
Bab 10 Kekuasaan Inggris (Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811-1816)
Seluruh tanah di area kekuasaan Raffles dianggap milik pemerintah, sedangkan petani diposisikan sebagai penyewa. Raffles lantas membentuk pegawai pajak yang langsung berhubungan dengan para bekel. Pembayaran pajak tidak lagi berupa hasil bumi, melainkan uang, biasanya mata uang perak. Dengan memakai uang, pertumbuhan ekonomi terpacu dan daya beli masyarakat ikut melonjak.
Raffles menciptakan sistem sewa tanah (land rent) berupa pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Raffles mengambil alih sistem perpajakan dan menarik sewa kios dan pajak barang lokal di pasar-pasar. Selain itu, ia juga mengenalkan pajak rumah tinggal atas pribumi yang tanah miliknya didirikan bangunan.
Bab 11 Hindia Belanda
Sistem Land Rent Raffles dinilai gagal oleh Belanda. Gubernur Jenderal Van den Bosch lalu menerapkan sistem Tanam Paksa, dimana rakyat Jawa wajib membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian, bukan uang, dengan harapan dapat dijual mahal di pasar Eropa.
Perkara beban pajak mendapat sorotan pengusaha kolonial di akhir masa penjajahan Belanda. Berbagai penyusutan dilakukan. Muncul kesan bahwa perubahan dalam komposisi penghasilan, terutama pajak pendapatan dan cukai, membuat beban pajak secara keseluruhan menjadi lebih adil. Cukai terutama dipungut dari hasil-hasil seperti gula, minyak tanah, korek api, dan tembakau yang telah diolah, yang kebanyakan dipakai oleh golongan menengah ke atas serta bermukim di kota dan desa.
Bab 12 Pendudukan Jepang 1942-1945
Jepang meneruskan Land Rent (sewa tanah) yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif. Bentuk pajaknya diwajibkan kepada desa dan bukan pada perseorangan. Pada masa inilah nama Land Rent atau Landrente itu diubah menjadi Land Tax. Pengelolaan pajak dilakukan oleh sebuah dinas di bawah Zaimubu dan melibatkan instansi pemungut pajak dan pembuat peraturan perundang-undangan perpajakan.
Jepang pun memberlakukan “usul pajak”, yaitu usul penetapan besarnya persentase pungutan pajak yang dikenakan pada desa. Menurut ordonansi, nilai usulan pajak bervariasi antara 8 hingga 20%. Tetapi dalam pelaksanaan, angka persentase pajak itu berkisar antara 6 hingga 16%.
Pemerintah Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi, padahal petani Jawa biasanya menghasilkan padi hanya untuk makan keluarga mereka sendiri. Pemerintah Jepang juga menetapkan pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya. Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi siapa saja yang memilikinya.
Pajak penghasilan diganti menjadi Pajak Perang, kemudian diganti lagi dengan nama Pajak Peralihan. Rakyat dibebani pajak yang berat untuk membiayai keperluan perang Jepang dan pemerintahannya di Indonesia.
Menjelang kemerdekaan, BPUPKI dibentuk dan dalam rapat-rapatnya membahas soal keuangan termasuk masalah pajak. Muhammad Yamin mengatakan bea dan cukai diatur sedemikian rupa sehingga penghasilan negara menjadi besar dan kesejahteraan tidak terganggu. Dr. Radjiman ikut sumbang saran bahwa keuangan negara terdiri dari pajak, dan pemungutannya harus diatur oleh hukum. Pajak baru tidak boleh menyengsarakan kehidupan rakyat jelata.
Bab 13 Revolusi Kemerdekaan 1945-1949
Para pendiri bangsa menyadari bahwa pembentukan negara tidak mungkin tanpa sistem perpajakan yang menyeluruh. Pajak menunjang berdirinya negara untuk berputarnya roda pemerintahan. Pajak kemudian didefinisikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung dari pemerintah, dan digunakan untuk pembiayaan umum.
Masalah pajak masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan, sebagai pondasi hukum perpajakan nasional. Dalam Pasal 23 yang memuat lima butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.
Sumber daya aparat pajak didapatkan melalui pembukaan kursus-kursus kontrolir pajak. Namun penyelenggaraan kursus kontrolir tahun 1947 itu belum banyak diikuti oleh orang pribumi. Kursus masih diikuti oleh orang-orang Belanda. Sampai pada tahun 1951, mulailah ada pribumi-pribumi yang dididik menjadi kontrolir.
Jawatan Keuangan kesulitan dalam pembiayaan pembangunan negara akibat revolusi mempertahankan kemerdekaan dan kurangnya pemasukan. Berbagai tarif seperti abonemen telepon, tarif pos, tarif kawat, serta restribusi berbagai pajak lainnya masih menggunakan tarif lama, yang berlaku sejak Jepang memasuki Nusantara di tahun 1942.
Bab 14 Republik Indonesia Era Presiden Sukarno
Menjelang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mei 1950, pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia atas pemungutan pajak-pajak yang penting.
Sesuai dengan semangat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada tahun 1952 dilakukan sejumlah perubahan istilah dalam organisasi perpajakan. Kata Directeur van Financien diubah menjadi Menteri Keuangan. Kata Hoofdinspeucteur van Financien diubah menjadi Kepala Jawatan Pajak. Kata Inspecteur van Financien diganti menjadi Kepala Inspeksi Keuangan. Kata-kata “Batavia” yang masih digunakan di beberapa sektor juga diganti menjadi Jakarta, dan mata uang Florin atau Gulden diganti menjadi Rupiah.
Selain pajak, pemerintahan Sukarno juga menetapkan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan lain, di antaranya dari bea cukai, denda-denda, dan hasil pengolahan kekayaan bumi seperti air, perusahaan negara, retribusi, dan lain-lain.
Pemerintah juga membentuk Panitia Perubahan Sistem Pajak. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan, di antaranya mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1957 terkait Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan.
Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah, pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Dua tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau Ipeda. Pemerintah juga mendirikan kantor kantor Inspeksi Keuangan di tingkat kabupaten dan kota sebagai usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang.
Menjelang akhir masa kepemimpinan Sukarno, muncul gagasan-gagasan sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari pajak. Di antara gagasan tersebut adalah pemerintah perlu memperbaiki pemungutan pajak dari keuntungan perusahaan-perusahaan negara. Mulai tumbuh pula pemikiran inovatif bahwa keadilan pajak harus ditegakkan.
JEJAK PAJAK INDONESIA
JILID 2: MASA ORDE BARU SAMPAI AWAL MASA ORDE REFORMASI
Bagian 1
Pajak Era Orde Baru Hingga Penerapan Sistem Self Assessment
Memasuki masa Orde Baru, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Kantor besar Direktorat Jenderal Pajak pindah dari Jalan Pintu Air, Jakarta, ke Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai tanggal 1 Februari 1973.
Ketika Dirjen Pajak dijabat Sutadi Sukarya, mulai muncul profesi konsultan pajak secara profesional. Pada 31 Oktober 1975, dibentuk Ikatan Konsulen Pajak Indonesia. Ikatan Konsulen Pajak Indonesia pada kongres 21 Nopember 1987 di Bandung diubah menjadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, disingkat IKPI.
Melalui Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Birokrasi pajak yang semula di dalam bidang moneter menjadi bidang perpajakan.
Terlalu banyaknya undang-undang, tidak memenuhi rasa keadilan, dan masih memuat aturan aturan yang berasal dari warisan kolonial, mendorong Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan reformasi 1983 undang-undang perpajakan yang ada. Pemerintah lantas mengundangkan lima paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan. Kelima undang-undang tersebut adalah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Meterai (BM).
Sistem perpajakan yang semula official assessment diubah menjadi self assessment. Perubahan sistem menjadi self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya dalam mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak juga dipersilakan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
Bagian 2
Perpajakan Indonesia Antara Tahun 1983 Hingga Awal Masa Orde Reformasi
Sejak tahun 1984, diterapkan pembaruan sistem pemungutan pajak. Era baru yang bernama Self Assessment System ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Reformasi Pajak yang diterapkan tahun 1983 itu disebut juga sebagai Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN).
Program komputerisasi tabel pegawai pun dilakukan. Pada 24 November 1984 dibentuk Kantor Pengelolaan Data dan Informasi (KPDO) di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran.
Tahun 1985, Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan. PBB termasuk jenis pajak yang sulit dalam administrasi dan efisiensi pungutan karena jumlah objek pajak yang sangat banyak. Penyempurnaan sistem pemungutan dilakukan tahun 1989 dengan membuat pembaharuan sistem administrasi penerimaan PBB melalui Sistem Tempat Pembayaran atau Sistep, yang diujicoba pertama kali di wilayah Kabupaten Tangerang. Sejumlah perubahan pasal pajak pun dilakukan.
Krisis moneter melanda sejumlah Negara termasuk Indonesia pada tahun 1997, dan memasuki puncaknya setahun kemudian. Banyak perusahaan bangkrut atau konglomerat yang terjerat utang dolar, namun penerimaan pajak justru makin bagus. Realisasi penerimaan pajak hingga 30 Maret 1998 mencapai Rp62,427 triliun. Padahal targetnya Rp56,144 triliun rupiah. Perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk ukuran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat.
Penggolongan terhadap pajak daerah kemudian disusun. Pajak Daerah Provinsi sebagai pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota sebagai pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Di dalam internal Direktorat Jenderal Pajak, terdapat sejumlah sumber daya manusia yang cukup paham bagaimana bentuk operasional kantor pajak yang sehat di luar negeri. Dari kondisi tersebut tumbuh keinginan untuk mengubah citra pajak. Reformasi perpajakan ikut masuk menjadi agenda utama IMF saat Indonesia berupaya menangani krisis moneter. Hal-hal itu menjadi cikal program Modernisasi Administrasi Perpajakan atau lazim disebut sebagai Modernisasi.
Hurri Junisar dan Dhimas Wisnu Mahendra, disarikan dari buku Jejak Pajak Indonesia, jilid 1 dan 2. Direktorat Jenderal Pajak